100% Yogyakarta: Pendataan di Atas Pentas
Oleh: Dendi Madiya
Sebuah pertunjukan teater bisa tersusun dari pertanyaan demi pertanyaan yang berlangsung di atas pentas.
Sebelum pertunjukan dimulai, terdengar musik bernuansa ceria memenuhi auditorium Concert Hall- Taman Budaya Yogyakarta yang diterangi pencahayaan. Penonton mengobrol dengan hangat dan cair sambil membuka-buka buku acara yang tebal serta memainkan telpon pintar masing-masing. Sesekali mereka mengambil foto selfie, tertawa bersama dan melangsungkan games yang terinstall pada cellphone. Anak-anak kecil tampak berkeliaran dengan rileks, bermain di atas kursi yang kosong, mengeluarkan celotehan-celotehan polos. Dari sini terasa bahwa identitas penonton kebanyakan merupakan warga yang bukan berasal dari kalangan teater.
Pada latar belakang panggung prosenium yang terbuka dan redup, terlihat lingkaran bulat berwarna biru dimana hal serupa dengan ukuran lebih besar mengalasi lantai panggung. Dari kondisi panggung ini ditambah musik yang riang, tertangkap kesan bahwa permulaan pertunjukan tidak berkehendak mengambil perhatian penonton secara penuh, dalam arti penonton dibiarkan sejenak mengalami keakraban satu sama lain dengan sedapat mungkin menjauhkan sugesti panggung. Sebuah permulaan yang seakan ingin berbicara atau mau menggiring penonton ke arah tema bahwa pertunjukan ini adalah tentang ‘Anda,’ tentang orang-orang yang hidup di Yogyakarta.
Istato Hudayana muncul dari tengah belakang, menghampiri mikrofon yang berada di tengah depan panggung, membuka pertunjukan gladi resik 100% Yogyakarta yang digelar pada tanggal 30 Oktober 2015, pukul 19.30 WIB itu. Pria berusia 38 tahun yang bekerja di Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini menceritakan pengalaman dari pekerjaannya sehari-hari, yaitu ‘menonton panggung’ warga Yogyakarta dengan segala karakteristiknya.
Untuk mendapatkan data, Istato bersama rekan-rekannya berkeliling dari pintu ke pintu. Sebagian warga menyambut dengan menyuguhkan makanan dan minuman. Tetapi tidak jarang, mereka berkeluh-kesah dan beraspirasi mengenai aspek pembangunan seolah mereka berhadapan dengan anggota dewan.
Sebaliknya ketika Istato bertandang ke daerah kota, dia menemui keadaan bahwa sebagian masyarakat sulit diwawancarai. Terlebih warga perumahan mewah. Mungkin mereka menganggap Istato sebagai salesman. Istato juga beranggapan warga kota lebih tidak mudah mempercayai orang lain.
Ada yang menarik di balik statistik, di balik pekerjaan Istato dalam mendata warga. Begitu berhasil memasuki setiap rumah, Istato mengajukan daftar pertanyaan yang panjang. Sebagian warga menjawab dengan mudah dan terbuka. Tetapi sebagian lagi begitu sulit memberikan jawaban, kurang terbuka bahkan keberatan untuk menjawab. Misalnya, ketika Istato bertanya tentang seberapa banyak kekayaan mereka atau omzet dari usaha mereka. Atau melalui pertanyaan ini: kapan kali terakhir berhubungan seks?
Lelaki yang berasal dari Purworejo itu memaparkan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah mengada- ada. Jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan digunakan oleh Pemerintah untuk merencanakan pembangunan.
Dengan gaya berbicara seperti berpidato secara rileks, Istato lebih jauh membeberkan data-data. Setiap hari ada 20 penduduk yang lahir pada saat 6 orang lain meninggal. Sementara jumlah pelajar di Yogyakarta sebanyak 856.979 orang yang berarti seperempat dari warga Yogyakarta. Sedangkan dari keseluruhan spesies burung di Pulau Jawa, 70 persen ada di Yogyakarta. Angka harapan hidup di Yogyakarta juga tertinggi di Indonesia yang menunjukkan bahwa orang-orang di kota ini mempunyai usia yang lebih panjang.
“Angka-angka ini ada di sekitar kita,” ujar Istato. “Sebenarnya menyenangkan untuk dibicarakan lebih jauh. Tapi saya yakin tidak semua orang suka dan akrab dengan angka-angka seperti ini.”
Penjelasan Istato itu seakan ingin menandaskan tentang statistik yang tidak melulu berkutat dengan angka-angka. Didalamnya terdapat lapisan-lapisan pemaknaan mengenai hidup, refleksi dari kenyataan dan tingkah laku masyarakat yang bisa dibaca. Statistik bisa menjadi bahan kreatifitas yang menarik, termasuk untuk diolah ke sebuah pertunjukan seperti 100% Yogyakarta ini. Pertunjukan yang bergerak dari reaksi berantai statistik: seorang warga dipilih lalu warga ini mengajak warga lainnya yang kemudian mengajak warga lain lagi dan begitu seterusnya hingga mencapai 100 orang. Setiap partisipan dipilih berdasarkan kriteria statistik yang melukiskan demografi Yogyakarta, meliputi umur, jenis kelamin, agama, komposisi keluarga, lokasi tempat tinggal, etnis, perbedaan budaya dan bahasa, tingkat pendidikan, status pekerjaan, perbedaan pendapatan, serta kemampuan yang beragam.
Orang-orang memperkenalkan dirinya masing-masing secara verbal. Dari sinilah terlihat narasi yang kompleks tentang warga penghuni Yogyakarta yang datang dari pekerjaan mereka, usia mereka, apa yang mereka suka, apa yang mereka tidak suka, asal-usul, hobi mereka, serta prinsip hidup. Sejak hal yang terkesan sepele hingga serius. Meskipun keseratus orang itu membeberkan informasi-informasi tentang dirinya secara sekilas tetapi setiap orang diberi focusing dengan teknik pembesaran gambar dari kamera video yang diproyeksikan ke lingkaran pada background panggung. Mereka membawa serta benda-benda yang mereka sukai atau barang-barang yang setia menemani mereka hidup. Dari sini, kita dapat melihat data-data statistik menjadi tubuh-tubuh yang nyata: warna kulit, penampilan, dandanan, cara berbicara, bahasa tubuh, pembendaharaan kata dan kegugupan di atas panggung. Para warga ini seolah diberi kesempatan untuk memiliki panggung tersendiri meskipun sejenak untuk menyuarakan ‘siapakah mereka.’
“Saya seniman tato dengan metode tradisional.”
“Saya tidak suka senioritas.”
“Saya berhenti dari politik praktis karena sulit menemukan kejujuran.”
“Saya laki-laki yang masih ber-KTP wanita.”
“Saya berasal dari organisasi Islam radikal yang menentang penistaan agama tetapi saya setia kepada bangsa dan negara.”
Tentu saja mereka individu-individu yang unik dengan karakteristik masing-masing. Tetapi, apakah yang menjadi khas Yogyakarta? Apakah yang menjadi isu terpenting di tengah warga Yogyakarta sekarang ini?
Mereka, warga Yogyakarta yang berada di atas pentas itu, menyebut diri sebagai ‘kelompok paduan suara yang tidak bisa selaras.’ Perbedaan pendapat atau jawaban diantara mereka terlihat dari respon terhadap pertanyaan demi pertanyaan yang bergulir dalam pertunjukan yang merupakan kerjasama antara Rimini Protokoll dengan Teater Garasi ini. Pertanyaan-pertanyaan itu dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, mulai dari pertanyaan umum, spesifik, sensitif, pertanyaan iseng atau humor, pertanyaan yang bersifat pribadi hingga persoalan ‘kontroversial."
“Siapakah diantara Anda yang rajin beribadah?”
“Siapa yang setuju Yogyakarta masih bertoleransi tinggi?”
“Apakah yang seharusnya dilakukan oleh Sultan?”
“Siapakah yang pasangannya pernah melakukan aborsi?”
“Bagaimanakah sebaiknya pendatang dari Indonesia bagian Timur bersikap di Yogyakarta?”
“Siapa yang pernah menyogok polisi?”
“Siapakah yang setuju Pemerintah harus meminta maaf kepada korban tragedi 1965?”
100% Yogyakarta mirip pertunjukan yang melakukan pendataan langsung di atas pentas. Begitu banyak pertanyaan yang bertaburan. Dengan demikian, sikap warga Yogyakarta terhadap sebuah pertanyaan atau permasalahan bisa dilihat langsung. Meskipun tanggapan mereka tergeneralisir ke dalam bentuk respon simplistik, seperti ‘saya’ dan ‘bukan saya,’ ‘setuju’ dan ‘tidak setuju,’ atau antara ‘saya termasuk bagian itu,’ dan ‘saya tidak termasuk bagian itu.’ Bahkan sampai ke tingkat mereka menentukan jawaban yang telah disediakan dimana hal ini mengingatkan pada bentuk ujian sekolah yang menyertakan pilihan ganda pada lembaran soal ujian. Perbedaan pendapat itu bisa secara tajam terlihat dengan dominasi tanggapan yang memihak ke salah satu jawaban. Tetapi pada pertanyaan lain, bisa juga terjadi jumlah respon yang merata antara ‘setuju’ dan ‘tidak setuju.’ Tentu saja tidak tertutup kemungkinan, seratus warga yang berada di atas pentas ini berbohong dalam menjawab atau tidak berkonsentrasi pada pertanyaan sehingga sering mereka mengubah sikap atau respon ketika merasa keliru memberikan tanggapan.
Inilah statistik yang dipentaskan. Namun, bukan berarti tontonan yang disutradarai oleh Helgard Haug dan Stefan Kaegi ini menjadi membosankan. Strategi pertunjukan tetap dilancarkan. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang menuju ke arah personal, panggung digelapkan. Warga menyalakan senter untuk menjawab soal-soal: Berapa banyak yang pernah menggunakan narkoba? Siapa yang pernah bercinta dengan sesama jenis? Pernahkah Anda melakukan hubungan seks dengan memberikan bayaran? Siapa yang membenci salah satu diantara 100 orang yang berada di panggung ini? Cahaya dari senter-senter ini juga diproyeksikan ke lingkaran bulat itu mirip penampakan imaji kunang-kunang dalam lorong yang gelap. Adegan ini terasa sebagai sebuah refleksi tentang bagaimana pun terbukanya iklim pergaulan sosial Yogyakarta bagi setiap orang, warga masih tetap menyimpan atau menjaga persoalan moral yang seakan tersembunyi. Penonton pun berdecak melihat kilatan-kilatan cahaya itu.
Reaksi penonton yang spontan memang terasa memenuhi pertunjukan yang merupakan bagian dari program JermanFest ini. Mereka tidak sungkan ikut mengomentari pertanyaan-pertanyaan yang digulirkan. Mereka juga tertawa lepas menanggapi tingkah laku warga di atas panggung. Ketika kesempatan diberikan untuk bertanya kepada warga, atau ketika dipersilakan untuk berfoto selfie bersama warga di atas panggung, penonton tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Penonton seakan terpancing untuk terlibat ke dalam pertunjukan dengan memberikan respon-respon reaktif seperti bertepuk tangan saat merasa terwakili oleh tanggapan warga atau menganalisa respon warga dengan rekan di sampingnya.
Kekikukan warga yang beraksi di atas panggung, mengingat mereka bukanlah aktor-aktris profesional, coba ditutupi atau direkatkan dengan jalinan musik dan sound efect. Efek suara itu dihadirkan dengan mengaitkannya kepada isi pertanyaan. Misalnya, “apakah Anda pernah diancam dengan pisau atau senjata lainnya?” diikuti oleh suara-suara pisau berdenting. Begitu pula persoalan kendaraan bermotor di Yogyakarta, ditingkahi oleh bunyi mesin otomotif menderu-deru.
Beberapa warga yang masih kanak-kanak ikut menghibur penonton. Pada sebuah titik pertunjukan, mereka meminta orang dewasa untuk meninggalkan panggung. Lalu mereka menguasai panggung dengan tema-tema yang berkaitan dengan dunia kecil mereka.
Aku bermain games selama dua jam dalam sehari. Aku punya kamar sendiri. Aku memiliki rahasia. Aku yakin suatu saat akan terlibat peperangan. Aku tidak mau menjadi seperti orang tuaku. Aku akan merawat orang tuaku saat mereka tua. Ketika mereka bersetuju, sebuah barisan pun terbentuk. Tetapi jika mereka tidak bersepakat, mereka memisahkan diri.
Rasa empati penonton juga terasa mengalir ketika seorang nenek menceritakan pengalamannya dipenjara karena tuduhan terlibat gerakan G30S. Nenek ini kemudian melanjutkan dengan menghantarkan pertanyaan: siapakah yang merasa terancam oleh komunisme? Begitu pula seorang ibu dengan putri kecil-nya yang secara jantan tanpa rasa takut terhadap stigmatisasi mengambil posisi di tengah saat pernyataan “kami menderita HIV-AIDS” muncul pada lingkaran bulat. Selain kedua tema itu, poin-poin dramatik pertunjukan yang digarap dramaturginya oleh Yudi Ahmad Tajudin ini juga dibangun melalui topik-topik: siapakah yang kehilangan sahabat terdekat belakangan ini? atau kami dibesarkan tanpa ibu.
Tema-tema dalam pertunjukan ini memang berserak tidak bulat. 100% Yogyakarta mempertontonkan kemungkinan lain dalam memperlakukan statistik dengan cara melakukan pendataan langsung di atas pentas menjadi semacam permainan yang atraktif melalui konteks tema yang beragam yang disalurkan lewat pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan yang direspon warga di atas pentas serta penonton pada bangkunya masing-masing. Penonton pun pulang barangkali dengan membawa kesan atau kesimpulan yang berbeda-beda atas pertunjukan ini. Mudah-mudahan dengan mengambil pelajaran mengenai pluralitas Yogyakarta dan bukan sekadar merasakan sebuah kebanggaan menjadi warga Yogyakarta.(*)


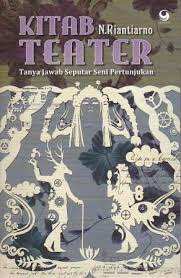
Comments
Post a Comment