CUT OFF (TO SEE, TO SEE YOURSELF, TO BE SEEN) Upaya Menuju Masa Depan
Oleh: Dendi Madiya
“Aku semacam kesal sekaligus menertawakan diriku sendiri sebagai seseorang yang dilahirkan di tanah ini tapi juga tidak pernah memiliki tanah ini.”
Riyadhus Shalihin, sutradara pertunjukan CUT OFF (TO SEE, TO SEE YOURSELF, TO BE SEEN), menambahkan kalimatnya, “Seseorang yang memiliki tanah hanya melalui KTP, hanya melalui akte kelahiran tetapi sebenarnya sejak kita dijajah lalu masuk Soeharto dan sekarang ini paska 98, apa sih yang sudah dihasilkan? Kita mau kembali kemana? Dengan CUT OFF ini, kita ingin merebut kembali ke masa depan. Ingin merebut dengan cara yang terkadang sangat sinis, terkadang juga sangat komedi dan terkadang juga bisa sangat pahit. Aku kira dengan pertunjukan CUT OFF ini, kita ingin memotong masa lalu sebagai sesuatu yang harus kita tendang untuk menuju masa depan.”
“Setidaknya dari pertunjukan ini, apa yang telah berlangsung pada hari-hari sebelumnya, pada masa lalu, dimana VOC, Hindia Belanda dan sekarang ada sesuatu yang terus sama, sejalan,” kata John Heryanto, salah satu aktor dalam pertunjukan ini. “Pada kemudian hari, saya berharap kita tidak perlu lagi mempertanyakan mau apa dan mau kemana kita akan pergi. Tapi setiap orang bisa menentukan pilihannya karena tidak semua orang di sini mengalami. Apalagi kita sebagai generasi paska reformasi yang tentu saja lahir pada zaman sekarang, tidak mengalami itu semua. Lebih banyak membaca tentang masa lalu, bukan mengalami. Apa yang kami alami adalah hari ini dan hari esok, tentu akan menjadi lain cara mengeksekusi apa yang terjadi.”
“Lebih harapan pada diri saya sendiri dulu,” ujar Hilmie Zein, pemain lain dalam pementasan CUT OFF. “Kita itu tidak hanya seperti luput dari sejarah, kita itu bagian dari sejarah itu, sejarah jalan itu dan kita menjalankan sejarah dari jalan-jalan itu. Dan sekarang kita berdiri dan berjalan. Harapannya lebih kepada aku mengerti apa yang terjadi dulu.”
Ganda Swarna yang juga bermain dalam CUT OFF menimpali, “Visi dari pertunjukan ini adalah bagaimana kami menyikapi sejarah itu dan hari ini. Kalau aku sendiri sangat sinis dan aku hanya sebagai seseorang yang sangat mentertawakan itu. Apa sih? Kenapa sih? Ada apa dengan sejarah? Terus kita ini apa yang sekarang ini? Ngomongin identitas apakah harus selalu ngomongin akar-akar kita? Identitas aku saat ini ya apa yang aku lahirkan saat ini. Aku ya aku hari ini.”
***
Arena pertunjukan yang bulat itu kosong. Tidak ada pemasangan set maupun properti atau tata artistik pertunjukan lainnya kecuali layar putih di bagian belakang yang dipasang mulai pada ketinggian sekitar 2 meter dari lantai panggung. Pada bagian akhir pertunjukan, layar ini menampilkan video ketiga aktor menertawakan diri mereka sendiri yang bergelimpangan di bawah dengan hanya mengenakan celana dalam berwarna merah. John, Hilmie dan Ganda melempari gambar mereka sendiri pada layar dengan gumpalan-gumpalan tanah merah yang sebelumnya berada di atas piring. Adegan ini seperti sebuah cara atau dorongan untuk selalu mengkritisi diri sendiri, melemparkan kembali kemuakkan individu kepada dirinya sendiri.
Tata artistik lebih diwakili oleh properti-properti kecil seperti sodet, piring, baju-baju, telur, tas ransel, tas koper, megafon dan ayam mainan. Sebuah strategi untuk memberi keleluasaan kepada ruang permainan. Ketiga aktor bermain tanpa terganggu pemasangan set. Tubuh para aktor mencoba menjadi sebuah tata artistik. Ganda bermain bersama koper, memberikan ‘nyawa’ kepada koper bahwa seolah-olah koper yang menarik tubuh manusia, bukan manusia yang menarik koper. Hilmi menjadi ‘manusia hibrid’ dengan tumpukan baju yang dikenakannya. Properti-properti ini menuntut sebuah pemaknaan lain ketika bersinggungan dengan tubuh aktor.
Penonton pada hari pertama kurang lebih 100 orang dari kapasitas ampitheatre Selasar Sunaryo Art Space (SSAS), Bandung, yang diperkirakan bisa menampung sekitar 200 penonton. Sedangkan penonton pada hari kedua berkisar 60 orang. Penonton ikut memberikan pengaruh terhadap pertunjukan. Ada bagian pertunjukan dimana para aktor berinteraksi dengan penonton lewat pengadeganan suasana pasar loak. Pada hari pertama, suasana interaksi itu lebih ‘hidup’ daripada hari kedua. Pada bagian ini, para actor dan pementasan seperti sedang ‘bertaruh’ untuk mulusnya ritme atau keberhasilan adegan-adegan berikutnya.
“Niat pertunjukan ini untuk menyajikan dampak globalisasi terhadap kehidupan badani kita sih pantas dipuji. Tapi, saya tidak yakin penampilannya membuat penonton menyadari hal tersebut,” demikian komentar Ari Jogaiswara, dosen Sastra Inggris Universitas Padjadjaran, Bandung. “Dari pementasan hari pertama, saya melihat bahwa penonton lebin fokus pada tindakan-tindakan di luar "normalitas" sebagai semacam dagelan. Jadi, urgensinya malah terlewat.”
“Saya tidak tahu apakah hal itu disebabkan oleh staging, termasuk penyutradaraan dan aktingnya,” terang Ari. “Atau karena memang penontonnya sudah dalam kondisi sedemikian rupa sehingga membutuhkan performansi yang lebih "mengganggu" supaya penonton "sadar."”
“Saya pikir setelah John memanggil anggota audiens masuk panggung akan lebih banyak interaksi dengan penonton,” harap Ari. “Tapi nyatanya seperti masih ada keengganan atau rasa sungkan untuk membuat penonton tidak nyaman.”
Visi pertunjukan yang berlangsung tanggal 4-5 Juni 2016 ini terasa kurang terwakili dalam ruang permainan. Penonton yang terlebih dahulu membaca tulisan Riyadhus pada Facebook barangkali sedikit kecele dengan apa yang tersaji pada pementasan CUT OFF ini. Hal ini terjadi karena tim kreatif CUT OFF melakukan pembatalan terhadap apa yang mereka riset. Mereka melakukan negasi terhadap buku-buku yang mereka pelajari sebagai basis reproduksi pertunjukan ini. Sebuah pembatalan yang diniatkan untuk menuju masa depan.*.(Dendi Madiya)



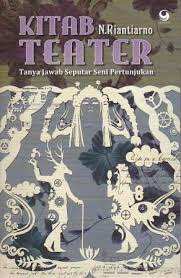
Comments
Post a Comment