Teater dan Gaya Hidup Urban
Oleh : Dendi Madiya
Teater bisa digunakan untuk memantulkan kehidupan. Kehidupan adalah sumber mata air pemicu kreatifitas dalam kesenian, tak terkecuali teater. Banyak lakon-lakon teater yang ditulis berdasarkan dorongan-dorongan dari peristiwa-peristiwa dahsyat dalam kehidupan di muka bumi ini. Waiting For Godot, misalkan, ditulis oleh Samuel Beckett karena kuatnya kehampaan yang dialami manusia paska Perang Dunia II.
Baik langsung maupun tidak langsung, apa yang terjadi dalam kehidupan di sekitar seniman akan membawa efek kepada karya-karyanya. Begitu pula dengan apa yang terjadi kini. Globalisasi yang menguat juga mengimbas kepada kreatifitas yang dilakukan para seniman.
Tak terkecuali kepada kelompok-kelompok teater yang hidup di kota besar, seperti Jakarta. Kelompok-kelompok itu kebanyakan beraktifitas di seputar Festival Teater Jakarta (FTJ) yang rutin diadakan setiap tahun. FTJ diadakan secara berjenjang, dengan terlebih dahulu diselenggarakannya babak penyisihan di lima wilayah kota administrasi Jakarta, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Tiga pemenang dari masing-masing wilayah itu akan dipertandingkan lagi di babak final atau tingkat Provinsi DKI Jakarta yang biasanya berlangsung bulan November-Desember setiap tahunnya.
Meskipun FTJ juga mengandung citra pembinaan terhadap kelompok-kelompok teater yang ada di Jakarta, tetapi pertunjukan-pertunjukan yang berlangsung dalam event ini tetaplah menarik untuk dibaca sebagai keberlangsungan kondisi sosial masyarakat Jakarta.
Denyut nafas Jakarta yang memiliki intensitas ketegangan yang signifikan dan ritme gerak produktifitas ekonomi yang mendesak ternyata tampak mempengaruhi tubuh-tubuh para aktor dalam panggung-panggung teater yang terjadi pada FTJ. Tubuh-tubuh urban menggeliat dalam gestur para aktor : mereka bergerak cepat, tergesa-gesa, dan mengucapkan dialog-dialog yang mengarah langsung hanya kepada tujuan-tujuan praktis belaka, sehingga kehilangan puitika. Dialog-dialog itu didominasi oleh teriakan-teriakan dan kata-kata umpatan khas kota besar yang bergejolak dalam hal persaingan kehidupan ekonominya.
Afrizal Malna, kritikus teater, pernah menulis “tubuh adalah ihwal yang mengalami bentukan budaya dari berbagai nilai, yang pada gilirannya memperlihatkan bagaimana manusia mengalami kesulitan dalam membaca tubuhnya sendiri. Semua peradaban manusia berkaitan langsung dengan kelebihan, keterbatasan maupun pengagungan tubuh manusia, sejak dari militerisme, seni, filsafat hingga ke kosmetika.”
Tubuh-tubuh aktor itu memang cenderung mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari tubuh kesehariannya. Tidak mudah bagi seorang aktor untuk menghadirkan tubuh kedua di atas panggung. Tubuh kedua itu adalah tubuh aktor yang sedang memerankan seorang tokoh di atas pentas dalam sebuah lakon. Diperlukan latihan yang maksimal dan intens untuk dapat meyakinkan penonton tentang peristiwa-peristiwa yang sedang digulirkan pada sebuah tontonan.
Hal itu juga berlanjut sampai kepada penataan artistik pertunjukan yang terkesan serba instan dan penuh warna-warni khas papan-papan reklame di jantung kota. Terutama mobilisasi pada kostum pemain. Kostum dibuat penuh dengan warna-warna yang mencolok. Belum lagi tubuh-tubuh yang berada di balik kostum tersebut yang nota bene terdiri atas tubuh anak-anak muda urban yang memamerkan kecantikan, ketampanan, sampai kepada tubuh-tubuh yang bercitra sensual. Memang pada forum FTJ ini bertebaran teaterawan-teaterawan muda yang mengasah dirinya tak henti-henti di tengah belantika perteateran Jakarta.
Di sisi lain, kontras terjadi pada tubuh-tubuh lusuh, kostum-kostum yang ditampilkan secara berdebu, penuh kotoran di sana-sini yang mencerminkan juga sisi urban Jakarta yang miskin, dan tertinggal kesejahteraannya. Kaya dan miskin memang menjadi fenomena hidup yang berlangsung berdampingan di Jakarta ini. Sebuah kenyataan sosial yang mengundang banyak lahirnya premanisme dan kriminalitas. Banyak kelompok teater di Jakarta yang tidak memiliki tempat latihan yang pasti dan tetap. Mereka berlatih secara informal di gelanggang-gelanggang remaja, taman-taman kota, sampai pelataran pinggir jalan raya. Latihan dasar teater yang mereka lakukan harus berkompromi dengan kondisi seperti itu.
Tradisi proses atau latihan teater yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sepertinya menjadi pertanyaan bagi kebanyakan kelompok-kelompok teater yang rajin mengikuti FTJ. Belum lagi jadwal latihan yang kerap harus bernegosiasi dengan skedul syuting sinetron yang juga dijalani sebagian aktor. Proses yang intens memang menjadi terganggu dengan keharusan memenuhi kebutuhan praktis, seperti mencukupi keperluan sehari-hari.
Inilah gaya hidup urban yang memberikan efek kepada panggung teater kita, meskipun beberapa teaterawan masih mencoba merefleksikannya dengan tetap bersikap ketat pada kaidah-kaidah estetika teater. Teater Syahid, misalnya. Pada repertoar mereka yang berjudul Kubangan (2005), sutradara Bambang Prihadi, usaha untuk merefleksikan kehidupan urban Jakarta berhasil mereka ciptakan secara cermat tanpa harus kehilangan keindahan.
Dalam repertoar itu, Teater Syahid menampilkan dimensi manusia urban yang penuh citra. Mulai dari masyarakat yang senang belanja, masyarakat yang berhura-hura belaka, individu-individu yang melakukan hal praktis semata sampai kepada masyarakat yang pelupa bahkan penuh dengan trauma. Pastinya, masyarakat yang serba bingung dan kehilangan prinsip hidup yang bergaul di kota besar. Sebuah masyarakat yang gagal memaknai kehidupan.
Hal tersebut direpresentasikan oleh Teater Syahid dengan bentuk tubuh aktor-aktornya yang gemetar, cepat, model-model yang cantik, tubuh-tubuh khas manekin, sampai kepada buasnya tubuh binatang untuk menampilkan Jakarta yang seperti belantara dengan hukum rimba-nya.
Sebenarnya banyak hal yang bisa diangkat dari kehidupan urban Jakarta untuk menjadi sebuah pertunjukan teater yang menarik. Hal ini tak terlepas dari kegigihan teaterawan Jakarta untuk dengan jeli dapat menangkap denyut nafas jantung kota dan memaknainya ke dalam bentuk-bentuk peristiwa panggung yang intens dan tidak sembarang. *
Dendi Madiya, sutradara Teater Omponk, Wakil Ketua Ikatan Teater Jakarta Timur (IKATAMUR), staf redaksi DRAMAKALA media komunikasi dan informasi teater, sekretaris panitia Festival Teater Jakarta Kota Administrasi Jakarta Timur 2012.


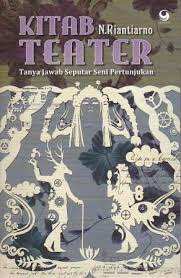
Comments
Post a Comment