WAWANCARA DENDI MADIYA DENGAN DINDON WS SEBUAH PERBINCANGAN TENTANG TEATER INDONESIA HARI INI
Tanggal Wawancara : 13 September 2011
Lokasi Wawancara : Rumah Dindon WS, Jl. Jatinegara Timur IV, Gg. Kober Kecil,
Rt 03/Rw 08 No. 8, Kel. Rawa Bunga, Jakarta Timur 13350
DENDI :
Bagaimana umumnya kondisi teater Indonesia sekarang ini?
DINDON :
Teater kita sekarang lebih semarak, lebih berwarna, bukan kualitas yang saya lihat. Seperti ada semacam ledakan baru. Dari wilayah lain turun ke teater, misalnya dari film. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang baru, yang membuat lebih berwarna sehingga lebih banyak pilihan. Di luar siapa dia, itu bukan persoalan. Seolah-olah orang darimana saja bisa masuk. Memang begitulah teater. Siapa saja boleh berekspresi, mencari duit, mencari keuntungan. Teater memberi peluang kepada siapa saja: politikus, pedagang…bisa juga memperlakukan teater untuk dirinya.
DENDI :
Apa pengaruh tokoh-tokoh seperti Rendra, Arifin C. Noer, terhadap teater kita sekarang?
DINDON :
Saya kira cukup kuat. Karena sejarah teater Indonesia tanpa menyebut Rendra atau Arifin, atau kalau kita lupakan mereka, kalau kita putus ingatan kita tentang mereka, maka ada sesuatu yang hilang. Pengaruh mereka cukup besar dalam sejarah teater kita. Karena sebelum ada naskah apa-apa, sebelum ada pertunjukan tahun 70-an, teater kita diantaranya ada Rendra, Arifin, Putu Wijaya. Mereka yang memberi inspirasi anak-anak muda. Termasuk saya. Saya juga terinspirasi oleh sejarah. Itu luar biasa. Saya kira kita banyak dipengaruhi oleh semangat hidup berteater orang-orang semacam Rendra, Arifin, Teguh Karya, Putu Wijaya.
Anak-anak teater sekarang mungkin tidak tahu siapa mereka, sosok mereka. Kalaupun mereka tidak pernah ketemu, tapi minimal secara literatur ada. Tapi mereka juga tidak menyentuh itu. Sehingga untuk membaca Kapai-Kapai, Aduh, Suku Naga, anak-anak sekarang agak kesulitan. Berat. Seperti sesuatu yang asing. Lebih baik membuat naskah sendiri atau memakai naskah luar.
Tapi kalau kita mau tertib, belajar dari sejarah. Bukan hanya karyanya, tapi spirit berkesenian mereka, dedikasi mereka terhadap dunia kesenian yang mempunyai arti penting, terutama untuk saya. Saya banyak dipengaruhi oleh para pelaku sejarah. Itu sumber inspirasi saya.
DENDI :
Bagaimana pengaruh para pendahulu itu dalam kerja artistik Teater Kubur?
DINDON :
Dulu saya pernah di Teater Ketjil, Teater SAE, teater Teguh Karya. Tapi sebagai seniman, karena saya belajar sungguh-sungguh, saya harus memposisikan diri saya ada dimana. Pengalaman-pengalaman itu banyak mendorong saya untuk mencoba berpikir ‘lu mau bikin apa?’
Saya banyak dipengaruhi oleh spirit kerja keras, intensitas, dedikasi, dan militansi mereka. Teater sebagai sebuah jalan hidup. Miskin atau kaya itu bukan persoalan, yang penting melakoni. Mereka berkesenian sebagai kerja ibadah. Seperti juga para seniman tradisionil. Saya juga mengartikan, menghayati teater seperti itu. Teater itu sudah seperti ibadah. Tidak ada urusan dengan rezeki. Rezeki itu urusan Allah. Tanpa sikap seperti itu, tidak mungkin bertahan lama. Orang-orang pelaku sejarah itu mempunyai ideologi berkesenian yang jelas.
DENDI :
Bisa diceritakan proses kreatif Teater Kubur?
DINDON :
Conditioning saya adalah latihan. Latihan menjadi conditioning buat saya, semacam upacara. Dalam latihan bisa muncul letupan-letupan apa saja. Bukan karena kita mau pentas, baru kita latihan. Tapi latihan yang menstimulir kita untuk bikin sesuatu. Artinya teater bukan hanya berorientasi pada produksi belaka. Produksi merupakan perkara gampang. Tapi, bagaimana menjalani teater dalam kehidupan kita sehari-hari itu bukan sebagai pekerjaan, melainkan ritual hidup kita. Nah, tiap ritual pasti punya sesuatu yang bermamfaat buat kita. Tempat kita berintrospeksi, berkontemplasi, kemudian di latihan itu kita berekspresi tentang persoalan-persoalan hidup, segala macam. Saya kira itu yang lebih penting di latihan. Latihan itu bisa menjadi kawah candradimuka, melahirkan Gatot Kaca yang sakti. Hanya di latihan.
Tergantung orang memaknai latihan itu apa. Kalau latihan hanya dimaknai untuk produksi belaka, sekadar begitu saja. Tapi kalau latihan dimaknai lebih daripada itu, maka tak ada kata hitung-hitungan waktu, kita bisa melakoni itu terus-menerus. Karena bukan atas nama kita mau pentas, tapi karena ada sesuatu yang kita jalani, kita cari, yang tak pernah selesai. Seperti kita sholat, tak ada selesainya. Itu saja. Ada kenikmatan lain. Mungkin dari sudut pandang pragmatis, hal ini agak ironis. Padahal yang dilatih itu bukanlah bagaimana membuat pementasan yang bagus. Tapi seluruh daya hidup kita, seluruh aspirasi kita, seluruh penghayatan dan kontemplasi kita, ada dalam latihan itu, terwujud. Wujudnya di latihan. Ibarat alimnya seseorang, bukan dari omongannya saja tapi ada syariat yang dijalankan terus-menerus. Syaratnya sholat. Teater syaratnya bukan sekadar latihan tapi terus mengolah, mengolah, dan mengolah. Semacam ada ritual itu.
DENDI :
Adakah naskah yang ditulis dalam pementasan Teater Kubur, terutama karya sendiri?
DINDON :
Ada. On/Off saya bikin naskahnya. Begitu pula Tombol 13, Sandiwara Dol, Danga-Dongo…
DENDI :
Apakah naskah ditulis dari rangsangan latihan atau sudah ditulis sebelum latihan?
DINDON :
Oke, saya menulis konsep di atas kertas, itu pekerjaan mengarang, yang bagi saya tidak terlalu sulit. Tapi saya tidak begitu percaya dengan cara seperti itu saya akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Saya mencoba membuka kemungkinan-kemungkinan di dalam ruang latihan. Segala kemungkinan bisa tercipta. Bisa saja dalam satu latihan itu cuma ada satu teks, satu puisi, satu kata. Jadi bukan persoalan teks-nya tapi bagaimana peristiwanya, persoalannya kita geluti. Kalau teks, itu gampang saja. Kadang-kadang teks baru selesai menjelang pementasan, tapi pementasannya sudah jadi. Jarang saya melangkah dari naskah jadi terlebih dahulu. Itu salah satu metode. Persoalannya sejauh mana kita merasakan enak dalam proses situ.
Bukan berarti saya tidak bisa membikin naskah. Tapi kalau sifatnya menggali, mencari, itu tidak hanya berhenti di otak. Kalau di otak, cukup di kamar saja kita mengarang, mengarang, dan mengarang. Tapi biasanya di ruang latihan itu kemungkinan-kemungkinan tak terduga banyak bermunculan karena kita langsung mengekspresikan, kita langsung melatih, mempraktekkan, dari satu kata, satu kalimat, mungkin dari tidak ada apa-apa, kemungkinan-kemungkinan tak terduga itu yang saya suka. Saya tak pernah menduga-duga akan membuat ini-itu. Jadi itu melatih kecerdasan intuisi kita juga.
Nah, kalau terbiasa mengarang, saya juga pernah. Tapi itu teater 17-an lah, saya kira model begitu. Sebetulnya sama saja, kalau hasilnya bagus, ya bagus saja. Ini masalah cara saja.
DENDI :
Bagamana dengan hal penyutradaraan?
DINDON :
Saya tidak bisa menyutradarai pemain-pemain Teater Kubur kecuali mereka sudah memasuki kawah candradimuka, saya sudah mengenal mereka, mereka sudah mengolah, kita sudah lama ber-jam session, baru saya bisa menyutradarai. Artinya di Teater Kubur, produksi pementasan menjadi nomer dua. Tapi bagaimana kita berlatih bersama, menumbuhkan sumber daya keaktoran, apa saja kita cumbui bersama. Ujung-ujungnya sebuah karya, itu merupakan hasil dari proses tersebut.
Aktor bisa bermain hebat, secara pribadi. Aktor-aktor Teater Kubur, saya latih bukan berarti tidak boleh kemana-mana. Silahkan saja kalau mau kemana-mana. Pada akhirnya mereka akan membawa diri mereka sendiri-sendiri. Dan aktor-aktor baru, pada mulanya mereka harus merasakan terlebih dulu atmosfir latihan yang betah, asik dan nyaman, baru mereka akan menjadi sesuatu. Biasanya saya latih demi untuk mereka juga. Saya percaya setiap orang punya kekuatan dan kelebihan yang luar biasa. Saya senang menemani, nongkrongin yang begituan.
Persoalan pentas nomer sekian. Gampang itu. Tapi bagaimana menumbuhkan teman-teman secara bersama, melihat potensi orang, itu yang paling penting untuk dilakukan.
DENDI :
Anda juga melukis dan memiliki beberapa buah lukisan Nashar. Bagaimana pengaruh pergaulan Anda dengan seniman-seniman bidang lain?
DINDON :
Seni adalah seni, baik itu tari, sastra, musik. Itu semua sudah menempel dalam diri saya sejak kecil. Sebelum saya kenal teater, sejak kecil saya sudah menari atau menyanyi. Saya menari sejak umur 6 tahun, karena saya ingin jadi Gatot Kaca. Musik juga. Seni rupa juga. Saya belum mengenal teater saat itu. Bacaan buku juga saya senang: Mahabharata, Bharatayudha. Kemudian saya berpikir, saya ini apa? Ternyata cocoknya di teater, tertampung semua. Potensi-potensi saya di bidang seni lain, sejak kecil kelihatan. Justru teater belakangan, dan itu tertampung semua dalam teater.
Jadi mayornya adalah teater meskipun awalnya saya merasa bisa menjadi penyanyi, pemusik, pelukis, saya juga bisa bikin lagu. Tapi dalam kesenian kita harus memilih, mayor kita apa? Teater, misalnya…
Tetapi itu semua ikut melatih saya: kepekaan ruang, kepekaan warna, kepekaan gerak, begitu juga kepekaan tulis-menulis. Itu memang adanya di teater, bermuara semua. Memang dari kecil, saya gemar semua. Sampai sekarang saya masih melukis. Seperti coretan di dinding rumah saya ini, waktu kecil saya seperti itu. Meskipun baru dicat, saya tak pernah melarang anak-anak saya coret di dinding. Dengan begitu, bakat mereka muncul karena saya tidak melarang, tidak memarahi.
DENDI :
Apa yang menjadi kendala dalam proses kerja kreatif Anda?
DINDON :
Saya tidak berhenti main teater karena masalah, karena kendala. Kalau teater itu serba pas-pasan, banyak kendala, itu memang habitatnya. Saya tidak merasa disusahkan karena main teater. Walaupun kenyataannya banyak masalah, tapi itu harus dilawan. Misal, persoalan ekonomi, persoalan apa saja, banyaklah…Kalau saya mau hidup nyaman, saya tidak akan bikin teater model begini. Di teater itu justru bagaimana kita menyelesaikan masalah. Hujan-angin bukanlah masalah dalam teater. Miskin, susah, bukanlah masalah. Karena kita bikin teater bukan karena sedang senang, tapi kondisi susah juga menjadi energi kreatif kita. Masalah itu bukan keluhan. Jadi, berteater itu jangan mengeluh. Kalau kita menggerutu terus, kita berbuat sesuatu jadi tidak ikhlas. Walaupun sedang susah, jangan bilang kita miskin, jangan menodong, jangan menadah. Tapi kita harus mengatakan bahwa semua itu bukan persoalan.
DENDI :
Apa pengaruh kondisi sosial-politik masyarakat terhadap kerja kreatif Anda?
DINDON :
Pada rezim Orde Baru, kita berhadapan dengan kekuasaan yang otoriter. Itu sangat mempengaruhi ekspresi teater di Indonesia. Dimensinya sangat politis, sangat berbau sosial, hampir semua orang menyuarakan seperti itu…protes…kalau tidak, seperti asyik sendiri. Tapi kondisi saat itu memang membuat orang bikin karya dengan bau protes, kritik sosial…Itu memang era Soeharto. Itu saya tandai dengan trilogi: Sandiwara Dol, Tombol 13, dan Sirkus Anjing.
Paska Soeharto, situasinya lebih besar. Kalau dulu sangat lokal, sekarang dimensinya global. Dimensi global yang mempunyai dampak kepada persoalan-persoalan lokal. Tentang, misalnya, kita menghadapi pasar bebas. Kalau dulu kekuasaan lokal, sekarang kita berhadapan dengan sistem besar. Dampaknya luar biasa. Nah, kalau kita tidak peka terhadap hal ini, seolah-olah teater itu sudah selesai. Kalau kita berpijak hanya seperti teater-teater tahun 70-an, sudah selesai. Sekarang, demokrasi sudah berjalan. Persoalannya lebih besar lagi, yaitu globalisasi. Itu persoalan saya sekarang.
Buat saya tak ada istilah teater kehabisan persoalan. Persoalan justru semakin gila. Makanya saya bikin On/Off, bagaimana Indonesia sebagai sebuah rumah yang pintunya sudah tercerabut. Orang bisa masuk lewat mana saja, binatang apa saja bisa masuk mempengaruhi kita. Nabi baru digelar di situ, Tuhan baru dijajakan di situ. Resikonya, jika kita tidak kritis terhadap situasi itu, Indonesia akan tenggelam. Indonesia tidak akan ada lagi, yang ada adalah manusia stereotip, yang lahir-diciptakan Barat. Pancasila sudah tinggal nama. Itu tantangan globalisasi. Ini berdasarkan hasil survey saya ke daerah-daerah. Sekarang yang otoriter adalah sistem besar itu. Kalau kita tidak masuk ke dalamnya, kita seolah-olah terbelakang atau negara biadab. Kita lihat Iran, Irak, Lybia, dicari-cari masalahnya, semuanya dihabisi.
Pola pikir kita, gaya hidup kita, mengikuti sistem besar itu. Tantangannya adalah identitas bangsa. Di kalangan menengah ke atas terlihat jelas pola pikirnya…gaya hidupnya…anak-anaknya dari kecil sudah diajari Bahasa Inggris…wah, Bahasa Indonesia-nya malah tidak bagus…banyak itu…saya hadapi sendiri…yang dilatih kecerdasan berpikir, tapi yang hilang adalah kecerdasan emosional…bahasa juga bisa mempengaruhi perilaku orang..
Akhirnya ada kesenjangan antara orang yang mampu mengejar sekolah dengan orang yang tradisional. Ada anak yang diprogram orang tuanya, ada anak yang ibunya saja tidak tahu mesti mengajari anaknya itu seperti apa…ada gap yang jauh…
Banyak kapitalis-kapitalis yang mendirikan sekolah ala luar negri di Indonesia ini. Kalau ekonomi kita makin hari makin bagus, mungkin kita akan lebih cepat menjadi orang lain.
DENDI :
Bagaimana tanggapan penonton Jepang terhadap On/Off?
DINDON :
Mereka senang walaupun tidak mengerti…tapi ada teks terjemahan sepanjang pertunjukan…Bahkan ada orang yang bisa menangkap secara visual…Ada yang merasa sedih, terpukul, ketika hadir adegan yang memang menyayat. Mereka cukup meng-appreciate karya yang saya bikin. Karena orang sana sebetulnya banyak mengetahui tentang saya. Makanya banyak seniman-seniman besar dari sana yang datang ke tempat saya, sutradara-sutradara hebat, peneliti…ya, saya kira timur itu ekspresinya hampir sama. Jepang sudah mapan dari segi teknologi dan manajemen teaternya. Saya lihat Jepang juga sudah bergeser, sangat Barat banget. Tak ada lagi orang yang mati-matian latihan atas nama ibadah. Kalau tak ada duit, mereka tak bisa latihan. Dan mereka main teater, harus punya sertifikat.
***

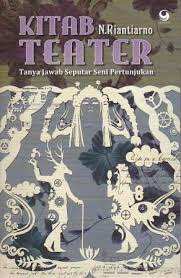
Comments
Post a Comment